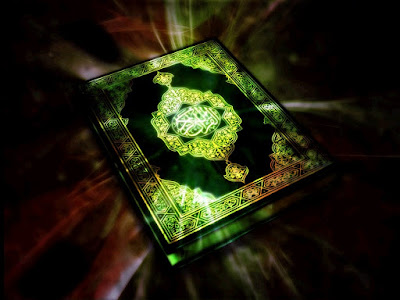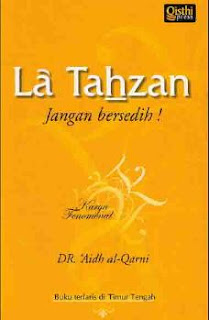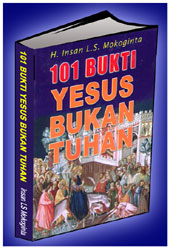ORANG MURTAD HARUS DIBUNUH?
Di tengah heboh berita Lukman Sardi pindah agama ke Kristen, ada sejumlah orang yang menegaskan bahwa orang murtad harus dihukum mati. Mereka mendasarkan diri pada hadits “Siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia (man baddala dinahu faqtuluhu).” Mereka juga mengklaim bahwa para ulama klasik sepakat tentang hukuman mati buat si murtad.
Seberapa meyakinkankah pandangan tersebut? Saya punya sejumlah keberatan:
Profesor Kamali menyebut sejumlah pemikir Islam generasi salaf yang berpendapat bahwa orang yang keluar dari Islam tidaklah diganjar dengan hukuman mati, melainkan mesti terus menerus diberi kesemptan untuk kembli ke Islam, karena selalu ada harapan bahwa mereka akan berubah pikiran dan bertaubat. Sebut saja nama-nama seperti Ibrahim al-Nakha’i , faqih(ahli fiqh) generasi tabi’in; Sufyan al-Tsauri, ahli hadist generasi tabi’ al-tabi’in yang digelari amir al-mu’minin dalam soal hadits dan pengarang buku kompilasi hadist tekenal, Jami’ al-Shaghir dan Jami’ al-Kabir; juga ahli fiqh empat mazhb seperti Imam Sya’roni dan Imam Syarakhsyi. (Lihat Mohammad Hashim Kamali, Freedom of Expression in Islam, hal. 93). Dengan kata lain, ahli-ahli hukum Islam sejak dulu berbeda pendapat tentang soal status orang murtad.
Siapapun yang mempelajari Ushul al-Fiqh tentu tahu bahwa penetapan hukuman hudud ( hukuman mati termasuk hudud) haruslah didasarkan pada ketentuan nash (teks rujukan) yang qath’iy (bersifat pasti), baik dalam hal pengertian yang dikandungnya (qath’iyyu al-dalalah) maupun dalam hal rangkaian sanad/rantai transmisinya (qath’iyyu al-wurud). Yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah Al-Qur’an dan hadits mutawatir(hadits yang diriwayatkan oleh puluhan orang dalam setiap mata rantai transmisinya).
Ketiga, klaim bahwa kaum murtad harus dibunuh karena kemurtadannya jelas bertentangan dengan spirit sejumlah ayat al-Qur’an tentang orang murtad ( seperti QS 3:90, 4:137, dan 2:217). Ayat-ayat ini memang menegaskan bahwa perbuatan murtad adalah suatu dosa yang serius, dan orang murtad akan dihukum Allah di akhirat. Tapi ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya hukuman mati di dunia buat mereka.
Perhatikan, ayat ini berbicara tentang orang yang bolak-balik murtad. Tapi hukuman yang disebut dalam ayat ini hanya hukuman yang berlaku nanti kalau di akhirat. Tidak disinggung adanya hukuman mati buat mereka di dunia. Logikanya, kalau tindakan murtad serta merta harus diganjar hukuman mati, tentu statemen Al-Qur’an tentang fenomena bolak-balik murtad menjadi tidak bermakna, karena si murtad tentunya sudah dipenggal sejak pertamakali keluar dari Islam. Dari ayat itu kita bisa menyimpulkan, tindakan murtad memanglah suatu dosa besar. Kalau si murtad tidak bertobat sampai meninggal, maka Allah tidak akan memberinya ampunan. Meskipun demikian, si murtad tetap punya hak untuk hidup dan selalu diberi kesempatan untuk bertobat hingga ajal menjemputnya.
Keempat, terdapat sejumlah hadist sahih lain yang bercerita tentang sejumlah orang yang keluar dari Islam pada masa Nabi, tapi beliau tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka. Misalnya, ketika Nabi masih tinggal di Makkah, ada seorang muslim bernama Ubaidillah bin Jahsh ikut serta dalam hijrah sejumlah sahabat Nabi dari Makkah ke Ethiopia. Sesampai di sana, Ubaidillah pindah ke agama Kristen dan tetap tinggal di Ethiopia. Nabi tentu tahu akan hal itu, tapi beliau ternyata tidak membunuhnya.
Contoh kasus lain: ketika di Madinah, ada seorang Arab badui datang menemui Nabi untuk menyatakan masuk Islam. Tapi beberapa saat kemudian, si badui minta supaya bai’at Islam-nya dibatalkan. Pada mulanya Nabi menolak, tapi si badui ngotot, dan akhirnya meninggalkan Madinah untuk kembali ke keyakinan pra-Islamnya. Meskipun demikian, Nabi juga tidak menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Kisah ini termuat dalam Sahih Bukhari:
عن جابر رضى الله عنه: جاء اعرابي الى النبي صلي الله علىه وسلم فباىعه علي الاسلام فجاء من الغدمحموما فقال: اقلني, فابى- ثلاث مرار. فقال: المدىنة كالكىر تنفي خبثها وىنصع طىبها.
Diriwayatkan dari Jabir R.A: seorang badui datang menemui Nabi dan melakukan bai’at masuk Islam. Tapi keesokan harinya dia datang dalam keadaan demam: batalkan bai’at Islamku, tapi Nabi menolak—berulang sampai tiga kali. Akhirnya Nabi berkata: Madinah ibarat alat peniup api, membuang yang kotor dan menjernihkan yang bersih darinya.
Dalam kaitan dengan empat poin yang saya paparkan di atas, ada baiknya di sini kita menyimak pandangan Mahmud Syalthut, pemikir Islam Mesir yang pernah menjadi rektor Universitas al-Azhar pd dekade 1950-an. Dalam kitabnya Al Islam: ‘Aqidatun wa Syari’atun, Mahmud Syaltut menulis:
“Mengenai hukuman mati untuk perbuatan murtad, para ahli fiqh mendasarkan diri pada hadits yng diriwayatkan Ibn Abbas:” Man baddala dinahu faqtuluhu” (Barang siapa berganti agama maka bunuhlah.) Hadits ini memunculkan pelbagai respon dari ulama. Banyak di antara mereka bersepakat bahwa hukuman hudud tidak bisa didasarkan pada hadits ahad.
Tindakan murtad semata tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi hukuman mati. Faktor utama yang menjadi penentu hukuman ini adalah adanya agresi dan permusuhan si murtad terhadap kaum beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan munculnya penghasutan melawan agama dan negara. Kesimpulan ini didasarkan pada banyaknya ayat-ayat al-Qur’an yang melarang paksaan dalam beragama.” (dikutip dalam Mohammad Hashim Kamali, Freedom of Expression in Islam, 1994, hal. 94-95).
Terdapat sekurang-kurangnya dua hal penting yang bisa kita garisbawahi dari pernyataan Mahmud Syalthut tersebut.
Kedua, statemen Syalthut “faktor utama yang menjadi penentu hukuman ini adalah adanya agresi dan permusuhan si murtad terhadap kaum beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan munculnya penghasutan melawan agama dan negara” sangat penting untuk ditekankan karena statemen itu menegaskan ‘illat (ratio legis, alasan hukum) yang menjadi alasan diterapkannya hukuman mati buat orang murtad. Yakni, bahwa hukuman itu terkait erat dengan adanya unsur agresi dan permusuhan dari si murtad.
Dengan kata lain, kaum murtad memang wajib diperangi kalau kemurtadan mereka dibarengi dengan tindakan memusuhi dan menyerang kaum beriman. Adapun kalau mereka keluar dari Islam tanpa disertai dengan tindakan semacam itu, maka hukuman mati dengan sendirinya tidak berlaku buat mereka. Ini sesuai dengan satu diktum al-qawa’id al-fiqhiyyah (legal maxims): Al-hukmu yaduru ma’a al ‘illati wujudan wa ‘adaman (berlaku atau tidaknya suatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya ‘illat (alasan hukum) yang mendasarinya).
Yang menarik, pendapat Mahmud Syalthut ini juga digemakan kembali oleh Tariq Ramadan, pemikir Islam Eropa kontemporer yang sekaligus juga cucu Hasan Al-Banna, pendiri garakan Ikhwanul Muslimin. Dalam satu wawancarnya yang pernah dimuat di Nesweek dan Washington Post, Tariq Ramadan menyampaikan pandangannya tentang apostasy dalam Islam sebagi berikut:
In the Islamic legal tradition, “apostasy” known as “ridda” is related to changing one’s religion and its injunction is mainly based on two prophetic sayings (ahadith) both quoted in sahih Bukhari (9,83 and 84): “The one who changes his religion, kill him” and another tradition noting that among the three categories of people who can be killed is “the one who leaves the community”. The great majority of the Muslim scholars, from all the different traditions and throughout history, have been of the opinion that changing one’s religion is prohibited in Islam and should be sanctioned by the death penalty.
Nevertheless we find, in very early studies and writings, several Muslim scholars having a different approach. The jurist Ibrahîm al-Nakha’î (8th), Sufyân ath-Thawrî (8th) in his renowned work on the prophetic tradition (Al-Jâmi’ al Kabîr, Al-Jâmi’ al-Saghîr) as well as the hanafi jurist Shams ad-Dîn as-Sarakhsî (11th) – among others- hold other views. They question the absolute authenticity of the two prophetic traditions quoted above. They also argue that nothing is mentioned in the Qur’an pertaining to this very sensitive issue and add that there is no evidence of the Prophet killing someone only because he/she changed his/her religion.
The Prophet took firm measures, only in time of war, against people who had falsely converted to Islam for the sole purpose of infiltrating the Islamic community to obtain information they then passed on to the enemy. They were in fact betrayers engaging in high treason who incurred the penalty of death because their actions were liable to bring about the destruction of the Muslim community and the two prophetic traditions quoted above should be read in this very specific context.
In light of the texts (Qur’an and prophetic traditions) and the way the Prophet behaved with the people who left Islam (like Hishâm and ‘Ayyash) or who converted to Christianity (such as Ubaydallah ibn Jahsh), it should be stated that one who changes her/his religion should not be killed. In Islam, there can be no compulsion or coercion in matters of faith not only because it is explicitly forbidden in the Qur’an but also because free conscious and choice and willing submission are foundational to the first pillar (declaration of faith) and essential to the very definition of “Islam”. Therefore, someone leaving Islam or converting to another religion must be free to do so and her/his choice must be respected.
Kesimpulan di atas juga didukung oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang tidak adanya paksaan dalam agama; tentang prinsip bahwa setiap orang punya tanggungjawab sendiri-sendiri untuk memilih mana jalan yang benar dan mana yang sesat; dan bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan risalah kenabian dan bukan untuk memaksa orang untuk menjadi mu’min, karena kalau Allah menghendaki, niscaya semua orang bisa saja Dia bikin menjadi beriman
Oleh :
elbowisblack.wordpress.com